Para raja dan masyarakat kerajaan Galuh, sebelum kedatangan Islam adalah pemeluk agama Hindu. Di antara bukti untuk hal tersebut adalah ditemukannya situs-situs purbakala yang merupakan tempat suci atau tempat-tempat peribadatan penganut agama Hindu. Salah satu peninggalan tersebut adalah Candi Cangkuang di desa Cangkuang, Leles-Garut yang diperkirakan dari abad VIII M. situs Batu Kalde di Pananjung, Pangandaran Ciamis yang diduga bahwa situs tersebut telah berdiri bangunan suci agama Hindu-Saiva. Di desa Sukajaya, Pamarican, Ciamis terdapat sebuah candi yang disebut Candi Ronggeng. Masih diwilayah Ciamis, tepatnya di daerah Mulyasari, Pataruman, Kotip Banjar, terdapat reruntuhan bangunan kuno yang disebut dengan Candi Rajegwesi. Situs lain yang tergolong luas terletak di tepi pertemuan dua sungai, yaitu sungai Citanduy dan Cimuntur di desa Karangkamulian, Cisaga, Ciamis. Oleh penduduk setempat situs tersebut dihubungkan dengan cerita rakyat Ciung Wanara.
Ada pula
suatu komplek kepurbakalaan yang cukup luas yang terdapat di Kawali, Ciamis.
Situs ini disebut Astana Gede. Di lingkungan kompleks yang terbagi ke dalam
beberapa halaman yang bertingkat ini terdapat enam prasasti baru.
Prasati-prasasti tersebut ditemukan pada halaman tertinggi dan relative berada
di pusat kompleks. Prasasti-prasasti Kawali menyebutkan bahwa tokoh raja yang
berkedudukan di Kadatuan Surawisesa yang bernama Prabu Raja Wastu yang
memerintah kerajaan dalam keadaan aman sejahtera dan dalam kurun waktu yang
cukup lama. Astana Gede di masa silam mungkin merupakan kompleks bangunan suci
yang ditata dengan halaman yang bertingkat-tingkat. Peninggalan lainnya ialah
situs Eyang Depok di desa Banjarharja, Kalipucang, Ciamis, yang berupa lahan
bertingkat dengan struktur bangunan dari tumpukan batu bekas reruntuhan sebuah
candi.
Pada masa
kerajaan Galuh, sekurang-kurangnnya terdapat empat jenis tempat yang disucikan
oleh masyarakat Sunda Kuna, yaitu Dewa Sasana, Kawikuan, Kabuyutan dan Pertapaan.
Dewa Sasana adalah tempat yang dikeramatkan karena dipercaya sebagai tempat
persemayaman para dewa yang di dalamnya terdapat pula bangunan suci untuk
pemujaan dewa. Kawikuan adalah tempat bermukimnya para wiku. Wiku dalam Bahasa
Sunda Kuna berarti pendeta atau dalam pengertian yang luas adalah kaum agamawan
yang telah mengundurkan diri dari dunia ramai dan menyepi untuk memperdalam
ilmu agama. Kawikuan merupakan bentuk pemukiman khusus yang relative luas, oleh
karena itu tidaklah heran apabila disebut dengan lurah kawikuan. Adapun
Kabuyutan adalah suatu tempat suci yang dikeramatkan dan dijadikan pusaka
masyarakat. Tentu saja ditempat itu pun bermukim para pendeta, namun tidak
sebanyak di Kawikuan. Kabuyutan Galunggung mereupakan kabuyutan yang paling penting
milik bersama masyarakat dan menjadi pusaka kerajaan. Adapun pertapaan adalah
tempat orang-orang melakukan tapa atau semedi.
Kepercayaan
masyakarat Galuh juga dapat dibaca dan ditelaah lewat naskah-naskah seperti Sewakadarma,
Jatiniskala, Kawih Paningkes dan Sanghyang Siksa Kanda Karesyan. Naskah-naskah
tersebut sudah ditransliterasi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia oleh para filolog maupun para ahli tentang kesundaan. Untuk
mengetahui isi naskah-naskah tertentu dengan adanya sejumlah naskah yang sudah
diterjemahkan.
Salah satu
naskah yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Galuh adalah naskah Sewakadarma
“pengabdian atau kebaktian terhadap darma” disusun oleh seorang petapa
perempuan bernama Buyut Ni Dawit yang bertapa di pertapaan Ni Teja Puru Bancana
di Gunung Kumbang. Oleh karena itu tidak mengherankan jika naskah itu
memberikan uraian tentang sebuah gisa “lesung” dengan istilah-istilah
yang khas untuk perempuan, seperti dikayasan, dyangiran, dan dipesekan.
Demikian juga uraian mengenai pakaian bidadari.
Berdasarkan
isinya, naskah Sewakadarma dapat dianggap sebagai salah satu bukti
mengenai pernah berkembangnya aliran Tantrayana di wilayah budaya Sunda pada
masa silam. Ajarannya menampilkan campuran aliran Siwa Sidhanta yang menganggap
semua dewa sebagai penjelmaan Siwa dengan agama Budha Mahayana. Capuran kedua
agama itu masih terjadil dengan “agama pribumi” mengingat ternyata unsure hyang
tetap dibedakan dari dewata walaupun tempat kediaman keduanya sama-sama
disebut kahiyangan.
Naskah
Sewakadarma berisi uraian mengenai kalopasan “kelepasan moksa”
yang menekankan kepada penggunaan bayu “tenaga”, sabda “ucapan”
dan hedap “tekad” yang sesuai dengan tuntutan dan petunjuk darma. Uarian
mengenai hal itu secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian. Bagian
pertama berisi ajaran yang menguraikan cara persiapan jiwa untuk
menghadapi maut sebagai gerbang peralihan ke dunia gaib. Di situ
dilukiskan peristiwa maut secara indah dan mengesankan karena maut merupakan
“pintu gerbang kelepasan” bagi jiwa. Bagian kedua melukiskan perjalanan jiwa
sesudah meninggalkan “penjaranya” yang berupa jasad dan kehidupan duniawi.
Ada
pandangan yang berbeda tentang moksa sebagaimana yang tersurat dalam naskah
Sewakadarma yang khas bersifat keagamaan. Perbedaan itu terdiri dari : Pertama,
naskah itu membicarakan kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan
memahami darmanya masing-masing. Kedua, bila tuntutan darma terpenuhi
dengan sempurna, tercapailah kreta “kesejahteraan dunia”. Ketiga, keberhasilan
dalam darma akan membuka kesempatan untuk moksa bagi siapa pun tanpa harus
menjadi “pendeta” dulu.
Ada
pula naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesyan yang terdiri dari dua
bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta sebagai kundangon urang reya
“pegangan orang banyak”, sedangkan bagian kedua yang disebut Darma
pitutur berisi hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan yang seyogyanya
dimiliki oleh setiap orang agar dapat hidup berguna di dunia. Uraian naskah itu
nampak sekali didasarkan pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan
bernegara.
Walaupun
naskah itu menyebutkan dirinya karesyan, isinya tidak hanya berkenaan
dengan kehidupan kaum agamawan. Bahkan lebih banyak yang berkaitan dengan
kearifan dan kewaspadaan hidup menurut ajaran darma. Ditinjau dari isinya, kata
siksa kandang karesyan mungkin dapat diartikan “aturan atau ajaran
tentang hidup arif berdasarkan darma”.
Naskah
Jatiniskala mengandung informasi mengenai ajaran keagamaan yang
memperlihatkan berbaurnya ajaran Hindu dengan ajaran pribumi. Bahkan dalam
naskah itu, nama-nama pribumi itu jauh lebih banyak, dan mereka yang memperoleh
derajat sebagai apsari “makhluk kayangan, pendamping dewa”
Naskah
Kawih Paningkes memuat ajaran keagamaan yang memperlihatkan bercampurnya
ajaran Hindu dengan ajaran pribumi. Nama-nama dewa dan istilah yang dikenal
dalam ajaran Hindu seperti dewa, dewata, sri, mahayoga, dan moksa, misalnya
ditemukan bersamaan dengan nama puhaci dan istilah yang dikenal dalam
kebudayaan asli Sunda : wirumananggay, kahyangan, sanghyang, dan puhun.
Dari
naskah-naskah lama berbahasa Sunda dapat diketahui bahwa orang sunda di
masa lampau sangat mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan
keagamaan, kebudayaan, dan akhlak. Hampir semua naskah menitikberatkan
uraiannya kepada segi kerohanian, bukan kepada hal-hal yang lebih bersifat
jasmani. Dalam empat buah naskah, yaitu naskah Sanghyang Siksa Kanda ng
Karesyan, naskah Sewakadarma, naskah Kawih Paningkes, dan
naskah Jatiniskala, misalnya membicarakan tentang segi-segi rohani itu
sangat menonjol, sedangkah yang bersifat jasmani disampaikan hanya sekedarnya
sebagai pengetahuan umum.
Sumber :
Apipudin. Penyebaran Islam Di Daerah
Galuh Sampai Dengan Abad Ke-17. Badan Litbang dan Diktat Kementerian Agama
RI. 2010
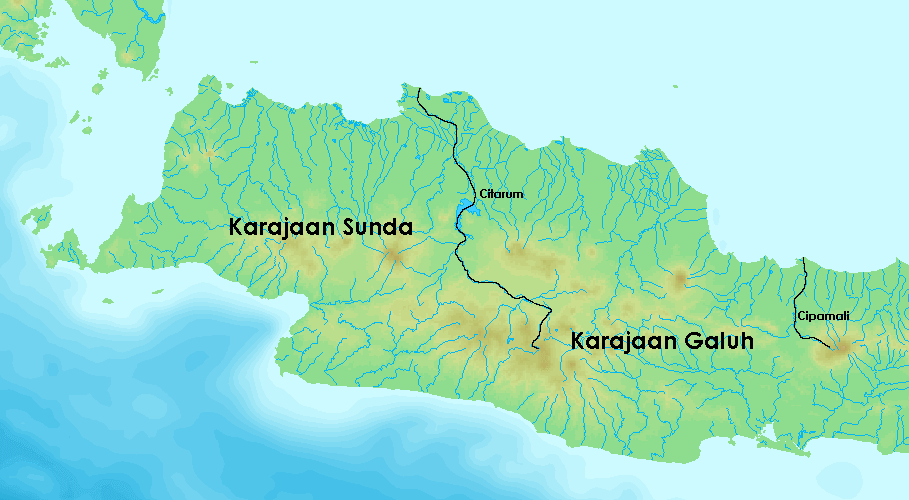











0 comments:
Post a Comment